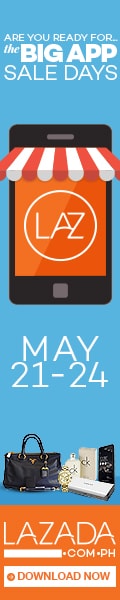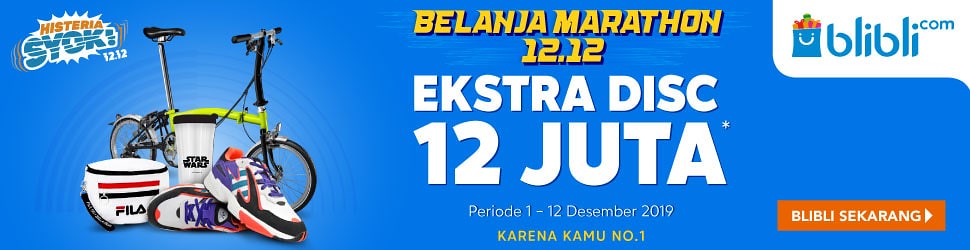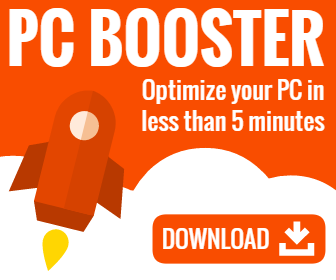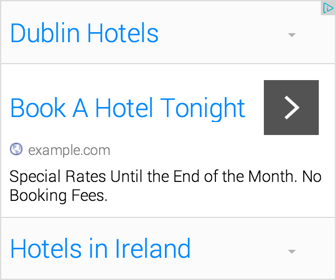Oleh : Gavin Asadit )*
Gelombang demonstrasi yang berlangsung pada Agustus hingga September 2025 meninggalkan catatan serius bagi pemerintah sekaligus bagi kita semua sebagai warga digital. Aspirasi publik adalah bagian esensial dari demokrasi—ia menjaga pemerintah tetap akuntabel dan membuka ruang koreksi yang sehat. Namun situasi di lapangan juga memperlihatkan sisi gelap komunikasi era platform: arus informasi palsu yang beredar masif di media sosial memantik emosi, membelah perhatian, dan dalam beberapa kasus memicu aksi anarkis yang merugikan banyak orang. Hoaks, video manipulatif, ajakan provokatif, hingga penggalangan dana digital yang menopang konten destruktif memperlihatkan bahwa provokasi kini bergerak lebih terstruktur dan canggih. Tantangannya bukan sekadar menertibkan jalan, melainkan juga menata ekosistem informasi agar publik mengambil keputusan dengan kepala dingin.
Dari pemerintah, sinyal respons sudah jelas. Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mencatat pola baru penyebaran narasi provokatif—mulai dari tayangan deepfake yang merekayasa adegan kerusuhan, poster ajakan turun ke jalan yang tak pernah benar-benar ada, sampai manipulasi potongan video yang seolah-olah membenarkan kekerasan. Menteri Komdigi Meutya Hafid menekankan pentingnya verifikasi sebelum membagikan informasi; seruan sederhana ini tampak remeh, tetapi itulah “rem moral” paling efektif di ruang digital: periksa sumber, baca utuh, tunda sebar. Di hilir penegakan hukum, Polri memperkuat langkah terhadap akun-akun yang terbukti menyebarkan hasutan. Menurut Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, negara berkewajiban hadir mencegah anarki—kehadiran yang bersifat melindungi ruang berekspresi damai, bukan mematikan kritik.
Ekosistem literasi digital menjadi kunci. Ketua Presidium Mafindo, Septiaji Eko Nugroho, mengingatkan bahwa hoaks adalah “bom waktu” yang mengandalkan reaksi cepat dan amarah spontan. Ia menyoroti beredarnya video “penjarahan” yang ternyata rekayasa dan gambar deepfake yang memproyeksikan situasi yang tidak pernah terjadi. Dalam pandangannya, publik yang terpancing emosi oleh konten semacam ini sesungguhnya sedang dimanfaatkan pihak yang mencari chaos, bukan solusi. Prinsip “lihat sumber, cari rujukan kedua, tunda sebar” adalah disiplin kecil dengan dampak besar; semakin banyak orang mempraktikkannya, semakin kecil peluang provokasi menjadi bola salju.
Dimensi generasi muda juga menentukan. Pengguna media sosial, sekecil apa pun pengaruhnya, memikul tanggung jawab etis terhadap dampak unggahannya. Figur muda seperti Jerome melihat peluang peran konstruktif: anak muda dapat menjadi pelopor narasi positif, mendorong diskusi berbasis data, mengedepankan kreativitas, dan mengalihkan energi dari benturan di jalan menuju advokasi digital yang aman, tertib, dan terukur. Aktivisme tidak kehilangan daya ketika meninggalkan kekerasan; justru ia bertambah daya karena mendapatkan legitimasi moral. Inilah inti etika kebebasan: kebebasan bernilai karena ditopang tanggung jawab.
Di ranah kebijakan, pemerintah menilai pandangan tersebut sejalan dengan upaya menjaga demokrasi tetap sehat. Demonstrasi adalah hak konstitusional, namun kebebasan itu mesti dijalankan dengan cara yang bertanggung jawab. Presiden menegaskan bahwa aspirasi rakyat tidak boleh tercampur dengan kekerasan atau hoaks, sebab campuran itulah yang merusak tujuan awal penyampaian pendapat. Sebab itu, kanal dialog—dari konsultasi publik, dengar pendapat, hingga tim teknis untuk merumuskan solusi—perlu dimanfaatkan maksimal. Keberanian menyuarakan tuntutan sebaiknya diimbangi kesabaran menyusun rincian kebijakan; suara keras yang membawa data dan argumen akan lebih mudah mengetuk pintu keputusan.
Dari sisi masyarakat sipil, ada tiga langkah praktis yang bisa segera diambil. Pertama, perkuat “kesadaran sumber”: biasalah menanyakan siapa yang bicara, dari mana data berasal, dan apakah ada koreksi resmi. Kedua, bangun “kelambatan produktif”: jeda beberapa menit sebelum menekan tombol bagikan adalah cara sederhana memutus rantai hoaks. Ketiga, dorong “moderasi berbahasa”: kritik keras tidak perlu dibingkai sebagai ajakan permusuhan; bahasa yang menghormati lawan bicara memperluas koalisi, bukan memperkecilnya. Tiga kebiasaan ini—sumber, jeda, moderasi—adalah vaksin sosial melawan provokasi.
Perguruan tinggi, komunitas profesional, dan organisasi keagamaan dapat memperkuat benteng ini. Modul literasi digital yang praktikal—misalnya latihan cek fakta, pengenalan tanda-tanda deepfake, dan etika distribusi konten—bisa diintegrasikan ke kegiatan rutin kampus dan komunitas. Platform digital juga dapat diajak bermitra memperjelas label konten kontekstual, memperketat monetisasi untuk akun pelanggar, dan memperluas akses ke data transparansi iklan politik. Pemerintah, pada gilirannya, dapat mempercepat infrastruktur pelaporan terpadu lintas platform agar proses klarifikasi lebih cepat dari ledakan rumor.
Dalam kacamata filsafat politik, keseimbangan antara kebebasan dan ketertiban adalah seni merawat ruang bersama. Kebebasan tanpa rambu menjerumuskan kita ke “hukum rimba digital”, sementara ketertiban tanpa kebebasan mematikan pembaruan. Pilihan yang dewasa adalah menguatkan rambu tanpa menutup jalan: menjaga demonstrasi tetap damai, mengawal arus informasi tetap jernih, dan mengubah kemarahan menjadi rancangan kebijakan. Demokrasi yang matang tidak anti-protes; ia justru mengandalkan protes yang etis sebagai energi korektif.
Pada akhirnya, menjaga kedamaian bukan hanya tugas negara, melainkan tanggung jawab setiap warga. Negara hadir menata aturan main dan menindak hasutan, masyarakat hadir menegakkan etika berbagi. Jika aspirasi disalurkan secara damai dan informasi dibagikan dengan kehati-hatian, Indonesia mampu melewati gejolak dengan kepala tegak—tanpa mengorbankan harmoni sosial yang menjadi fondasi persatuan. Di era ketika satu unggahan bisa mengubah suasana kota, kebijaksanaan kolektif adalah nama lain dari keberanian: berani menahan jari, berani memeriksa fakta, berani memilih jalan damai agar suara yang benar-benar penting—suara warga—sampai ke ruang kebijakan tanpa tersesat di kabut provokasi.
)* Penulis adalah Pemerhati Masalah Sosial dan Kemasyarakatan